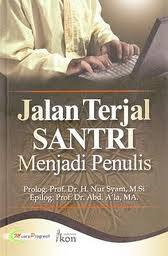17/01/2011
17/01/2011Judul: Dialog Problematika Umat
Penulis: KH. MA Sahal Mahfudz
Penerbit: Khalista Surabaya dan LTN PBNU
Cetakan: I, Januari 2011
Tebal: xii+464 hal.
Peresensi: Ahmad Shiddiq *
Orang mengenal Kiai Sahal sebagai sosok kiai yang bersahaja. Namun, di balik kesederhanaannya, pengasuh Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati, Jawa Tengah ini memiliki keluasan ilmu yang jarang dimiliki oleh kiai kebanyakan. Tidak salah kalau kemudian dalam penelitian yang dilakukan Dr Muzammil Qomar, beliau disejajarkan dengan nama-nama besar semisal (alm) KH Achmad Shiddiq sebagai tokoh yang mempunyai pemikiran liberal. Bahkan beberapa waktu yang lalu kiai bernama lengkap Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz ini di anugerahi Doctor Honoris Causa (Dr HC) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta karena keteguhannya dalam fikih Indonesia.
Kiai Sahal adalah figur, pemimpin, ekonom, pendobrak kebekuan, kemunduran, kemiskinan, dan latar belakang. Sosok multidisipliner dan dinamisator kalangan pesantren serta Nahdlatul Ulama, dua lembaga yang membesarkan juga dibesarkannya. Sebagai ulama, Kiai Sahal tidak diragukan lagi kapasitas keilmuan agamanya, khususnya penguasaan terhadap kitab kuning atau al-turast al-islami. Kapasitas keulamaan ini terlihat dari karya yang sangat banyak meliputi berbagai aspek keilmuan.
Dunia pesantren maupun akademisi begitu memberikan apresiasi sekaligus kepercayaan kepadanya untuk bisa mentransformasikan keilmuan di berbagai tempat, termasuk lewat berbagai media yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk mengisi rubrik khusus sebagai kolumnis maupun forum dialog atau bathsul masail, yang diantaranya menjadi buku ini.
Dengan pemikiran yang tajam, ia mampu memberikan solusi secara kronologis, jelas, transparan dan sistematis dari setiap problema umat yang disodorkan kepadanya. Disini dibahas tuntas problematika mengenai bersuci, shalat, puasa Ramadhan, zakat dan pemberdayaan ekonomi umat, haji, rumah tangga, antara tuntutan ibadah dan rekayasa teknologi, akidah-akhlak, mengagungkan kitab suci, makanan, dan etika sosial.
Bagi Kiai Sahal, fiqh bukanlah konsep dogmatif-normatif, tapi konsep aktif-progresif. Fiqh harus bersenyewa langsung dengan ‘af al al-mutakallifin sikap perilaku, kondisi, dan sepak terjang orang-orang muslim dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun mu’amalah (interaksi sosial ekonomi). Kiai Sahal tidak menerima kalau fiqh dihina sebagai ilmu yang stagnan, sumber kejumudan dan kemunduran umat, fiqh justru ilmu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan riil umat, oleh karena itu fiqh harus didinamisir dan revitalisir agar konsepnya mampu mendorong dan menggerakkan umat Islam meningkatkan aspek ekonominya demi mencapai kebahagian dunia-akhirat.
Kontekstualisasi dan aktualisasi fiqh adalah dua term yang selalu dikampanyekan Kiai Sahal baik secara ‘qauli (teks) melalui acara seminar, simposium, dan sejenisnya. ‘kitabi (tulisan) dikoran, majalah, makalah, serta fi’li (tindakan) dalam bentuk aksi langsung di tengah masyarakat dengan program-program riil dan konkret yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam buku ini, jelas bahwa umat Islam sekarang dalam sebuah kebingungan menghadapi dunia modern. Dunia modern yang selama ini dibanggakan oleh masyarakat, ternyata malah menyisakan problem yang memprihatinkan. Dunia modern diagung-agungkan dengan berbagai kecanggihan informasi, transportasi, dan alat-alat teknologi lainnya ternyata gagal membentuk pribadi muslim yang luhur dan mampu mengorbankan serta pengabdian dirinya untuk masyarakat. Semua orang dengan bangga berkata sebagai orang modern, tetapi ternyata hatinya berpenyakit dan begitu menyedihkan bila ditinjau dalam segi agama.
Bagi Kiai Sahal, kebenaran sesuatu selain dari dalil-dalil naqliyah juga bisa berasal dari dalil aqliyah. Memang al-Qur’an dan al-Hadits merupakan sumber hidayah yang paling utama dan esensial bagi umat Islam. Namun peran akal juga tidaklah kalah penting. Dalam beberapa ayat, peran akal sangat istimewa bahkan orang-orang yang diberi ilmu derajatnya tinggi dihadapannya. Hasil pemikiran sains yang berkembang sekarang dapat kita jadikan sebagai petunjuk untuk mempertebal keimanan asalkan tidak bertentangan dengan ketetapan syariah. Dengan demikian, sains dan ilmu pengetahuan yang bersumber dari akal pikiran bukan bid’ah, atau kemusyrikan dan kekufuran. Bahkan sains dan ilmu pengetahuan diperintahkan Allah untuk dipelajari dan dikembangkan. Ini penting karena berguna meningkatkan kualitas hidup manusia dan bahkan bisa mempertebal iman.
Pergulatan panjang Kiai Sahal dalam lapangan fiqh sosial ini ternyata membawa perubahan besar dan dahsyat dalam lapangan pemikiran pesantren dan akademis (perguruan tinggi), ekonomi kerakyatan, kebudayaan, kelembagaan (pesantren dan NU), dan politik kebangsaan. Dari kalangan peasntren, pemikiran progresif fiqh sosial Kiai Sahal mendorong santri dan Gus-Gus muda pesantren belajar secara mendalam ilmu usul fiqh dan mengembangkan untuk merespons tantangan modernisasi sekarang ini. Lalu muncullah pemikir-pemikir muda pesantren dan NU progresif, transformatif, dan inovatif, dan mereka jauh lebih berani keluar mainstream pemikiran NU, tetapi tetap dalam koridor ahlusunnah wal jamaah.
Dengan demikian, dilihat dari kacamata akademik pesantren Kiai Sahal mampu menyediakan informasi yang komprehensif dan cermat dalam menganalisis serta akurat dalam menyajikan jawaban-jawaban umat. Rais Aam PBNU ini, telah lebih maju dengan memberikan tawaran gagasan-gagasan segar terkait problematika umat dengan pengembangan qawaid ushuliyah untuk menjadikan fiqh sebagai bagian dari peradaban modern.
Wal-hasil buku setebal 464 ini dapat menjadi inspirasi kaum muda dalam mengembangkan lebih jauh gagasan-gagasan ulama sekaliber KH MA Sahal Mahfudz dan tentunya patut menjadikan buku ini, rujukan menemukan jawaban hukum Islam yang berkaitan problematika umat. Selain mudah dibaca oleh siapa saja, buku ini memberikan jawaban nuansa berbeda yang disesuaikan dengan zaman kontemporer. Waallahu a’lamu bi al-shawab.
*) Penulis Santri Pesantren Luhur Al-Husna dan Redaktur Pena Pesantren Surabaya
Retrieved from: http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=26969