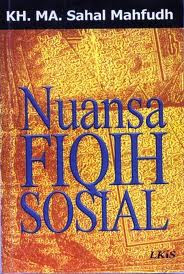23/06/2009
Oleh Sri Sofiati Umami *Sebelum kelompok-kelompok teologis dalam Islam lahir, Ahlussunnah Wal Jamaah (selanjutnya disebut Aswaja) adalah umat Islam itu sendiri. Namun setelah kelompok-kelompok teologis muncul, Aswaja berarti para pengikut Abu Hasan al-Asy’ari dan Abu Manshur al-Maturidi.
Dalam pengertian terakhir ini, Aswaja sepadan dengan kelompok-kelompok teologis semisal Mu’tazilah, Syiah, Khawarij dan lain-lain.
Dalam sejarahnya, kemunculan kelompok-kelompok ini dipicu oleh masalah politik tentang siapakah yang berhak menjadi pemimpin umat Islam (khalifah) setelah kewafatan Rasulullah, Muhammad SAW. Setelah perdebatan antara kelompok sahabat Muhajirin dan Anshor dituntaskan dengan kesepakatan memilih Abu Bakar sebagai khalifah pertama, kesatuan pemahaman keagamaan umat Islam bisa dijaga. Namun menyusul huru-hara politik yang mengakibatkan wafatnya khalifah ketiga, Utsman Bin Affan, yang disusul dengan perang antara pengikut Ali dan Muawiyah, umat Islam terpecah menjadi kelompok-kelompok Syiah, Khawarij, Ahlussunnah dan –disusul belakangan, terutama ketika perdebatan menjadi semakin teologis oleh—Mu’tazilah dan lain-lain.
Aswaja melihat bahwa pemimpin tertinggi umat Islam ditentukan secara musyawarah, bukan turun-temurun pada keturuan Rasulullah SAW sebagaimana pandangan Syiah. Aswaja memandang keseimbangan fungsi nalar dan wahyu, tidak memposisikan wahyu di atas nalar sebagaimana pandangan Mu’tazilah. Aswaja melihat manusia memiliki kekuasaan terbatas (kasb) dalam menentukan perbuatan-perbuatannya, bukan semata disetir oleh kekuatan absolut di luar dirinya (sebagaimana pandangan Jabariyah) atau bebas absolut menentukan perbuatannya (sebagaimana pandangan Qadariyah dan Mu’tazilah).
Pada wilayah penggalian hukum fiqh, Aswaja (sebagaimana diwakili oleh Imam yang empat: Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) bersepakat menggunakan empat sumber hukum: Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas; dan tidak bersepakatan dalam menggunakan sumber-sumber yang lain semisal: istihsan, maslahah mursalah, amal ahl al madinah dan lain-lain.
Setelah melalui evolusi sejarah panjang, Aswaja sekarang ini menjadi mayoritas umat Islam yang tersebar mulai dari Jakarta (Indonesia) hingga Casablanca (Maroko), disusul oleh Syi’ah di Iran, Bahrain, Lebanon Selatan; dan sedikit Zaidiyah (pecahan Mu’tazilah) di sejumlah tempat di Yaman. Dengan mengacu pada ajaran Muhammad Bin Abdulwahhab, rezim Saudi Arabia berafiliasi kepada apa yang disebut Wahabi. Sementara di Asia Selatan (Afganistan dan sekitarnya) reinkarnasi Khawarij menemukan tanah pijaknya dengan sikap-sikap keras dalam mempertahankan dan menyebarkan keyakinan.
Di Indonesia, Aswaja kurang lebih sama dengan nahdliyin (sebutan untuk jamaah Nahdlatul Ulama), meskipun jamaah Muhammadiyah adalah juga Aswaja dengan sedikit perbedaan pada praktik hukum-hukum fiqh. Artinya, arus besar umat Islam di Indonesia adalah Aswaja.
Yang paling penting ditekankan dalam internalisasi ajaran Aswaja di Indonesia adalah sikap keberagamaan yang toleran (tasamuh), seimbang (tawazun), moderat (tawassuth) dan konsisten pada sikap adil (i’tidal). Ciri khas sikap beragama macam inilah yang menjadi kekayaan arus besar umat Islam Indonesia yang menjamin kesinambungan hidup Indonesia sebagai bangsa yang plural dengan agama, suku dan kebudayaan yang berbeda-beda.
Ada dua kekuatan besar yang menjadi tantangan Aswaja di Indonesia sekarang ini dan di masa depan: kekuatan liberal di satu pihak dan kekuatan Islam politik garis keras di pihak yang lain. Kekuatan liberal lahir dari sejarah panjang pemberontakan masyarakat Eropa (dan kemudian pindah Amerika) terhadap lembaga-lembaga agama sejak masa pencerahan (renaissance) yang dimulai pada abad ke-16 masehi; satu pemberontakan yang melahirkan bangunan filsafat pemikiran yang bermusuhan dengan ajaran (dan terutama lembaga) agama; satu bangunan pemikiran yang melahirkan modernitas; satu struktur masyarakat kapital yang dengan globalisasi menjadi seolah banjir bandang yang siap menyapu masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia.
Sebagai reaksinya, sejak era perang dingin berakhir dengan keruntuhan Uni Soviet, Islam diposisikan sebagai “musuh” terutama oleh kekuatan superpower: Amerika Serikat dan sekutunya. Tentu saja bukan umat Islam secara umum, namun sekelompok kecil umat Islam yang menganut garis keras dan secara membabi-buta memusuhi non muslim. Peristiwa penyerangan gedung kembar pusat perdagangan di New York, Amerika, 11 September 2001, menjadikan dua kekuatan ini behadap-hadapan secara keras. Akibatnya, apa yang disebut ‘perang terhadap terorisme’ dilancarkan Amerika dan sekutunya dimana-mana di muka bumi ini.
Yang patut digaris bawahi: dua kekuatan ini, yang liberal dan yang Islam politik garis keras, bersifat transnasional, lintas negara. Kedua-duanya menjadi ancaman serius bagi kesinambungan praktik keagamaan Aswaja di Indonesia yang moderat, toleran, seimbang dan adil itu.
Gempuran kekuatan liberal menghantam sendi-sendi pertahanan nilai yang ditanamkan Aswaja selama berabad-abad dari aspeknya yang sapu bersih dan meniscayakan nilai-nilai kebebasan dalam hal apapun dengan manusia (perangkat nalarnya) sebagai pusat, dengan tanpa perlu bimbingan wahyu. Gempuran Islam politik garis keras menghilangkan watak dasar Islam (Aswaja lebih khusus lagi) yang ramah dan menyebar rahmat bagi seluruh alam semesta.
Dua ancaman riil inilah yang mengharuskan Aswaja di Indonesia untuk mengkonsolidasi diri, merapatkan barisan, memvitalkan kembali modal nilai-nilai luhur yang diturunkan dari ajarannya dan pengalaman sejarahnya. Karena sifat dua tantangan ini yang mondial, maka reaksinya pun harus mondial.
Sejauh ini, ikhtiar itu ada. Nahdlatul Ulama melalui forum ICIS (International Conference of Islamic Scholars) sudah tiga kali menggelar pertemuan para ulama-intelektual dunia Islam di Jakarta untuk tujuan dimaksud: tujuan luhur mengembalikan Islam sebagai rahmat bagi semua.
Ke dalam, penggairahan masjid sebagai pusat peradaban dan institusi perawatan nilai-nilai juga disadari semakin penting dilakukan. Manakala masjid berfungsi merawat Aswaja, maka serbuan dua ancaman tadi bisa dilawan pengaruhnya.
Tentu saja, penyikapan yang komprehensif harus diupayakan secara menerus. Nilai dilawan nilai. Instrumen dilawan instrumen. Sudah saatnya, pada tingkat instrumen, organisasi penyangga Aswaja di Indonesia memiliki misalnya, stasiun televisi, production house untuk membuat film berbasis nilai-nilai Aswaja, perusahaan penjaga kemandirian ekonomi umat dan segala institusi baru lainnya agar penyikapan komprehensif dan efektif bisa dilakukan secara maksimal. Wallahua’lam
* Penulis adalah guru madrasah, tinggal di Pondok Pesantren Ta’limussibyan al-Manshuriyah Bonder, Lombok Tengah, NTB
Sumber : http://www.nu.or.id
http://aswaja-nu.blogspot.com/